Ki Le-Olam Hasdo
Tab primer

Barang siapa membaca Mazmur 136, saya yakin, akan segera melihat ciri khas mazmur ini. Ia mempunyai 26 ayat. Dan setiap ayat selalu diakhiri dengan kalimat yang sama: "... bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya". Atau, dalam bahasa aslinya: "ki le-olam hasdo". Ada 26 ayat! Berarti tidak kurang dari 26 kali "kile-olam hasdo".
"Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik!
Ki le-olam hasdo.
Bersyukurlah kepada Allah segala allah!
Ki le-olam hasdo.
Bersyukurlah kepada Tuhan segala tuhan!
Ki le-olam hasdo.
..."
Dengan mudah dapat kita duga, bahwa mazmur ini dipakai di dalam ibadat jemaat. Pemimpin ibadah mengucapkan atau menyanyikan sebuah kalimat, kemudian seluruh jemaat menjawabnya bersama-sama: ki le-olam hasdo. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bentuk ini disebut litani. Karenanya, Mazmur 136 sering disebut orang sebagai Litani Agung.
Kalimat yang pendek dan diucapkan secara berulang-ulang, tentu membuat jemaat dapat menghafalnya dengan mudah. Ki le-olam hasdo. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
Mudah dihafal dan diucapkan, namun tidak berarti mudah dipahami dan dihayati.
***
Penginjil Matius menulis, "Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-murid-Nya ke Bukit Zaitun" (26:30). Nyanyian pujian itu mereka nyanyikan dalam perjamuan malam yang terakhir. Dan, kemungkinan besar nyanyian yang mereka nyanyikan itu adalah Litani Agung itu. Ki le-olam hasdo. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Padahal Anda tentu tahu apa yang menanti Yesus di Bukit Zaitun itu. Di situlah, di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Hati-Ku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Ngerinya jalan penderitaan yang mesti Dia lalui. Pahitnya piala kematian yang mesti Dia cucup dengan mulut-Nya. "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku ...."
Tidak kurang dari Yesus sendiri kini harus berhadapan dengan misteri doa yang tidak terkabulkan. Pintu telah diketuk, tetapi ia tetap tertutup.
Setelah Getsemani, mulailah jelas apa yang harus Dia hadapi. Malam yang singkat, tetapi terasa begitu panjang. Bukan ayunan cambuk yang terutama menyayat hati-Nya, tetapi pengkhianatan murid-Nya sendiri. Lalu penyangkalan orang yang pernah dekat dengan Dia. Sinar mata kebencian kepada orang yang begitu mengagungkan kasih dan menekankan pengampunan.
Dan akhirnya, kematian salib. Eloi, Eloi! Lama sabakhtani? Ya Tuhan- Ku, Ya Tuhan-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?
Yang sulit kita pahami ialah, bagaimana kita harus menghubungkan "ki le-olam hasdo" dengan "Eloi! Eloi! Lama sabakhtani?" Bagaimana mungkin sesuatu yang dimulai dengan nyanyian yang begitu khidmat, "Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya", bisa berakhir dengan ratapan yang begitu tragis, "Ya Tuhan-Ku! Ya Tuhan-Ku! Mengapa Engkau meninggalkan Aku?"
Bukankah itu kerap kali merupakan pengalaman Anda dan saya: kesenjangan antara ungkapan-ungkapan liturgis yang manis dan kenyataan hidup yang keras?
Akan tetapi, "ki le-olam hasdo" memang bukan hanya ungkapan liturgis yang manis. "Ki leolam hasdo" adalah suatu ungkapan iman, tidak lebih dan tidak kurang.
Menghadapi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, iman itulah yang harus berperan. Iman itulah yang mampu mengatakan "bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya", juga ketika mulut kita meratap, "Ya Tuhanku! Ya Tuhanku! Mengapa Engkau meninggalkan Aku?"
Tidak, Saudara, keduanya jangan kita pisahkan, apalagi kita pertentangkan. "Ki le-olam hasdo" justru memperoleh maknanya di dalam "Eloi! Eloi! Lama sabakhtani?" "Eloi! Eloi! Lama sabakhtani?" justru memperoleh jawabannya di dalam "ki le-olam hasdo".
Sekali lagi, hal ini memang tak dapat kita pahami dengan analisa intelektual kita. Ia hanya dapat kita pahami di dalam terang iman.
Jangan Anda katakan, yang satu adalah harapan dan yang lain adalah kenyataan. Tidak! Keduanya adalah kenyataan.
"Ki le-olam hasdo" adalah kenyataan. "Eloi! Eloi! Lama sabakhtani" adalah kenyataan. Bila toh ada perbedaan antara keduanya, maka perbedaan itu terletak di sini. "Ki le-olam hasdo" adalah kenyataan yang hanya dapat dilihat oleh kacamata iman kita.
Dan betapa keduanya itu kita butuhkan. Berteriak "Eloi! Eloi! Lama sabakhtani?" saja, akan membuat kita putus asa dan tidak berdaya. Sebaliknya, berkata "ki le-olam hasdo" saja, hanya akan membuat kita terbang ke angkasa tanpa mampu menginjak bumi.
"Ki le-olam hasdo" memberikan pengharapan. Tetapi pengharapan yang tidak membawa kita keluar dari kenyataan.
"Ki le-olam hasdo" memberikan kepada kita pengharapan untuk menghadapi kenyataan, mengatasi kenyataan.
***
Alangkah bahagianya dan alangkah tegarnya, orang yang dapat
menyanyikan Litani Agung ini dengan seluruh penghayatannya.
Hidup ini tak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan.
Ki le-olam hasdo.
Hidup ini tak selalu memberikan apa yang kita harapkan.
Ki le-olam hasdo.
Hidup ini tak selalu membawa kita ke tempat yang kita suka.
Ki le-olam hasdo.
Semboyan kosongkah ini, Saudara? Bisa jadi, bila ia hanya berhenti menjadi ungkapan liturgis yang manis.
Namun, saya jamin ia akan merupakan kekuatan luar biasa, bila ia benar-benar merupakan ungkapan iman yang tulus.
Ia tidak menjanjikan jalan yang mudah. Akan tetapi, ia memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melangkah.
Hidup kita tak akan pernah lepas dari tantangan. Akan tetapi, bukan tanpa pengharapan.
Hidup kita tak akan pernah bebas dari pergulatan. Akan tetapi, bukan tanpa kemenangan.
| Diambil dari: | ||
| Judul buku | : | Mengapa Harus Salib |
| Penulis | : | Pdt. Eka Darmaputera, Ph.D. |
| Penerbit | : | Gloria Graffa |
| Halaman | : | 36 -- 41 |

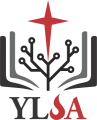

 sabda_ylsa
sabda_ylsa Yayasan Lembaga SABDA
Yayasan Lembaga SABDA sabda_ylsa
sabda_ylsa Selengkapnya
Selengkapnya SABDA Alkitab
SABDA Alkitab
 Podcast SABDA
Podcast SABDA Slideshare SABDA
Slideshare SABDA